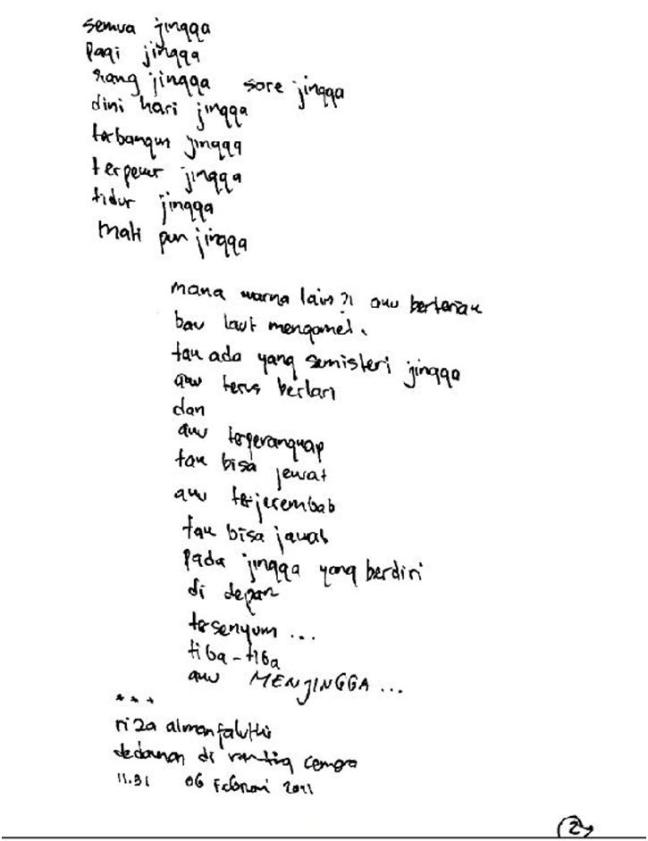KARENA IA ADALAH PENGGANTI YANG LEBIH BAIK
Hari sudah semakin sore, jum’at (29/4) itu rekonsiliasi dengan Pemohon Banding di gedung Pengadilan Pajak belumlah usai seluruhnya. Kami hanya dapat menyelesaikan untuk satu sengketa pajak saja mengenai objek-objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
Kami sepakat untuk melanjutkannya di pekan yang akan datang. Tentunya bagi tim kami, yang penting ada panggilan dari Pengadilan Pajak, kalau tidak ada itu kami tidak akan datang. Jangan dilupakan, kami tidak akan datang juga walau sudah ada panggilan kalau tidak ada surat tugas dari direktur kami. Ini semata-mata agar kami tidak dianggap sebagai petugas banding liar dan tetap dalam kerangka melaksanakan tugas negara—bukan tugas pribadi.
Saya bergegas menuju Jalan Senen Raya untuk menghadang Bus Jurusan Senen Cimone yang melewati Stasiun Gambir—karena dari sana saya akan pulang naik kereta rel listrik (KRL). Untuk menghentikan bus itu saya harus menunggu lama di seberang Hotel Oasis Amir. Bisa saja saya naik bajaj atau ojek motor atau juga naik taksi. Tapi pilihan itu akan saya ambil jika waktunya mepet dengan jadwal KRL yang saya naiki. Dan untuk hari itu waktu yang saya miliki masih banyak.
Kemudian tak sengaja mata saya melihat gedung tinggi di ujung sana. Tempat Pengadilan Pajak berada. Saya sempatkan untuk mengambil gambarnya dengan menggunakan kamera hp.

Gedung bercat putih itu adalah Gedung Dhanaphala. Di sana selain Pengadilan Pajak adalah tempat berkantornya para pegawai Direktorat Jenderal Anggaran.
Bus itu tiba dan tak sampai 10 menit sampai di depan Stasiun Gambir. Sesampainya di stasiun itu segera saya beli tiket dan naik ke lantai 1. Saya mencari tempat duduk di sana. Tak biasanya saya demikian. Di hari-hari sebelumnya kalau sudah beli tiket saya langsung naik ke lantai dua dan menunggu KRL datang di peron 3-4.
Saya pikir waktunya masih lama dan pasti akan ada pemberitahuan kalau KRL Pakuan Ekspress itu tiba di Stasiun Gambir dari Stasiun Kota. Makanya saya santai saja duduk-duduk di bangku lantai 1. Ada sekitar 20 menit saya di sana. Untuk sekadar menelepon, sms-an, dan tentunya melihat Monas dari kejauhan. Sepertinya emas yang ada dipuncaknya itu tak berkurang satu gram pun.
Ketika ada pengumuman bahwa KRL Pakuan datang, saya segera naik ke lantai 2 dengan santainya. Eh, pas betul, setibanya di atas, KRL Pakuan itu sudah nongkrong di jalur 3 dengan pintu yang sudah tertutup dan kemudian berangkat lagi. Saya gigit jari. Saya ketinggalan kereta. Tega nian KRL itu untuk tidak membuka pintunya barang sejenak agar saya bisa ikut dengannya.
Aneh, seharusnya pengumuman kedatangan KRL diberitahukan sebelum KRLnya datang di Stasiun Gambir bukan? Atau pada saat KRL sudah berangkat dari stasiun terdekat. Nah, ini benar-benar tidak ada. Tiba-tiba diumumkan kalau KRLnya sudah tiba di jalur 3. Atau sebenarnya ini salah saya? Seharusnya pula kalau sudah tahu jadwalnya jam segitu ya segera naik ke atas. Tak perlu tunggu pengumuman. Nanti akan alasan begini: “Memangnya jadwal KRL selama ini tepat waktu?” Ya sudahlah akan banyak argumentasi yang muncul.
KRL ini memang tidak berhenti di Stasiun Citayam tetapi ia berhenti di Stasiun Bojonggede. Dari sana saya harus menunggu KRL arah baliknya yang menuju ke Jakarta untuk nantinya turun di Stasiun Citayam.
Keterlambatan ini harus ditebus dengan 20 menit menunggu kereta berikutnya. Apalagi sore itu Stasiun Gambir sudah mulai penuh karena banyaknya pemakai jasa kereta api yang ingin pulang kampung. Maklum akhir pekan. Jadi suasananya tambah semrawut.
Eh, kekecewaan ini terobati juga. Dari pengumuman yang ada, KRL berikutnya itu bisa berhenti di Stasiun Citayam. Jadi tak perlu harus ke Stasiun Bojonggede dan balik lagi. Dan betul ketika sampai di Stasiun Citayam waktu tibanya tidak berbeda jauh bila naik KRL yang meninggalkan saya itu. Hmm…
Saya kembali memikirkan sesuatu. Hingga pada sebuah ujung bahwa seringkali kita menyesali dan merutuki nasib karena sesuatu yang diharapkan lepas dari tangan kita. Padahal Allah sudah menggariskan kalau memang yang diharapkan itu bukan untuk kita, bisa jadi karena tidak baik untuk kehidupan kita di dunia atau setelahnya. Pun, karena Allah sudah mempersiapkan yang lain lagi sebagai penggantinya, bahkan lebih baik.
Sore itu saya mendapatkan yang terakhir.
***
Riza Almanfaluthi
dedaunan di ranting cemara
bahagia ditemani sepanjang perjalanan
10.40 01 Mei 2011
Tags: pengadilan pajak, senen raya, hotel oasis amir, Cimone, kereta rel listrik, gambir, citayam, bojonggede, pajak penghasilan pasal 23, pakuan, jakarta, gedung dhanapala, direktorat jenderal anggaran, departemen keuangan,


 MATANYA ABADI
MATANYA ABADI Kelihatan sih kalau sudah tua, wajahnya tak sesegar dulu. Sudah mulai tirus. Mungkin kalau ibarat manusianya sudah mulai ada keriputnya. Tapi swer ketika saya memfoto itu kucing, gak ada tuh namanya keriput sama uban. Dan yang pasti matanya yang dicelak hitam itu, abadi bo…
Kelihatan sih kalau sudah tua, wajahnya tak sesegar dulu. Sudah mulai tirus. Mungkin kalau ibarat manusianya sudah mulai ada keriputnya. Tapi swer ketika saya memfoto itu kucing, gak ada tuh namanya keriput sama uban. Dan yang pasti matanya yang dicelak hitam itu, abadi bo…