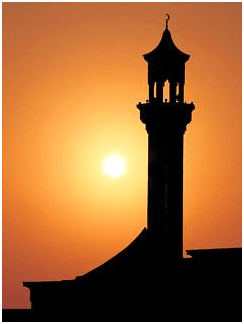PEMERINTAH… JANGAN KORBANKAN KAMI
Menjelang lebaran haji tahun 2010 ini terasa sekali
oleh saya—sebagai ketua takmir—berat dalam memutuskan sesuatu.
Masalah klasik sebenarnya. Kapan puasa sunnah arafahnya dan kapan shalat Idul Adhanya. Tahun 2007 lalu yang pelaksanaannya berbeda kayaknya tidak ada masalah dan kami enteng-enteng saja melewatinya. Untuk kali ini sepertinya tidak.
Ada Jama’ah yang berpendapat hari Senin puasanya karena sudah menjadi keputusan pemerintah Arab Saudi wukuf di arafah pada hari itu. Jadi shalat Idul Adhanya hari Selasa. Jama’ah yang lain berpendapat bahwa kita kudu ikuti apa kata pemerintah. Pemerintah sudah menetapkan tanggal 10 Dzulhijjahnya pada hari Rabu sehingga Shalat Idul Adhanya jatuh pada hari itu juga dan Puasa Arafahnya pada hari sebelumnya yaitu pada hari Selasa.
Ada lagi jama’ah lain yang berpendapat bahwa kita ikuti penetapan hari raya Idul Adhanya pada hari Rabu namun puasanya mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi karena puasa Arafah berpatokan pada pelaksanaan wukuf di Arafah.
Saya harus ambil keputusan karena saya pikir dari kesemua pendapat itu ada banyak ulama yang mendukungnya. Satu yang tetap menjadi pertimbangan saya adalah sesungguhnya menjaga persatuan umat Islam wajib hukumnya. Sedangkan pelaksanaan puasa Arafah dan shalat Idul Adha adalah sunnah. Tentunya mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah itu adalah lebih utama.
Karena kebanyakan dari kita terkadang sulit dalam menentukan prioritas. Terbukti kalau shalat Idul Adha ataupun Idul Fitri banyak yang datang berbondong-bondong datang ke masjid padahal sehari-harinya tidak pernah datang sama sekali. Sepertinya shalat ‘Id adalah sebuah kewajiban sehingga kalau tidak melaksanakannya terasa kurang afdol atau gimana gitu…
Begitupula dalam penentuan waktunya, perbedaannya akan menjadi pertengkaran yang berujung saling berdebat, membenci, dan timbul benih-benih perpecahan. Padahal puasa Arafah dan shalat ‘Id Qurban hukumnya sunnah belaka (maksimal adalah sunnah mu’akadah, sunnah yang amat dianjurkan). Tak perlu mengorbankan sesuatu yang wajib dengan mengunggulkan yang sunnah. Seperti contoh yang lainnya adalah lebih mementingkan shalat tahajud tapi shalat shubuhnya kesiangan ditambah tidak berjama’ah di masjid.
Dengan pertimbangan kaidah keputusan pemerintah menghapuskan perbedaan maka saya ambil keputusan melaksanakan pendapat yang ketiga. Yakni untuk melaksanakan shalat Idul Adha di Masjid Al-Ikhwan pada hari Rabu dan dipersilakan untuk melaksanakan puasa Arafah pada hari Senin.
Dengan ambil penetapan tersebut saya harap tidak ada masalah bagi yang tetap ngotot berlebaran pada hari Selasa dan tidak mau melaksanakan shalat Idul Adha pada hari Rabu, namun dirinya tetap punya peluang melaksanakan puasa Arafah pada hari Senin. Lebih mementingkan puasa daripada shalatnya dengan alasan balasan yang diberikan Allah sungguh luar biasa. Dihapuskannya dosa kita setahun kebelakang dan satu tahun ke depan. It’s ok.
Pun saya harapkan penetapan ini tidak masalah bagi jama’ah yang berpendapat shalat Idul Adha pada hari Rabu, karena kebanyakan orang juga jarang untuk mengamalkan puasa Arafah terkecuali mereka yang paham dengan agama ini dan sunnah-sunnahnya.
Pertimbangan yang lebih penting lagi bagi saya adalah seperti sedikit diuraikan di atas yakni kaidah disunnahkannya meninggalkan sesuatu yang sunnah demi menjaga persatuan. Di mana apabila terjadi pertentangan antara wajib dan sunnah, maka yang dilakukan adalah yang wajib, walaupun harus meninggalkan yang sunnah. Karena maslahat persatuan lebih besar daripada maslahat melakukan sunnah.
Dr. Abdul Karim Zaidan menukil dari An-Nadawi yang mengilustrasikan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad saw dalam penerapan kaidah ini. Beliau tidak mengubah bangunan Ka’bah, karena dengan membiarkannya seperti yang sudah ada dapat menjaga persatuan.
Sahabat Abdullah bin Mas’ud tidak sependapat dengan Utsman bin Affan yang melaksanakan shalat dalam perjalanan secara sempurna (itmam). Tetapi ditengah perjalanan Ibnu Mas’ud ra melaksanakan shalat itmam dan menjadi makmum di belakang Utsman ra. Ketika ditanya tentang perbuatannya itu, Ibnu Mas’ud ra berkata, “perselisihan itu buruk.”
Memaksakan shalat Idul Adha pada hari Selasa di tengah pemahaman masyarakat yang mayoritas Nahdliyin dikhawatirkan timbulnya fitnah bagi umat. Yaitu fitnah terjadinya perpecahan. Jika memang dipastikan tidak ada fitnah, maka dipersilakan saja untuk untuk melaksanakan shalat Idul Adha pada hari Selasa. Anda yakin maka silakan pakai kaidah ini: keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan (alyaqiinu laa yazuulu bisysyakki). Dan pada kondisi yang saya alami di sini saya masih ragu.
Jalan dakwah masih panjang. Tujuan jangka pendek tak bisa mengorbankan tujuan jangka panjang. Perlu menghitung kekuatan dan risiko yang timbul. Selagi tetap memaksakan pendapat kita yang menurut kita paling rajih tetapi dengan membuat masyarakat kita lari sedangkan di sana masih terbuka peluang adanya pilihan lain yang syar’i, maka tujuan dakwah yang hendak dicapai akan menjadi semakin panjang lagi. Lalu mengapa kita memaksakan diri?
“Insya Allah tahun depan kita pikirkan kembali,” kata saya kepada para jama’ah yang menginginkan shalat Idul Adhanya pada hari Selasa.
By the way, inilah resiko menjadi rakyat kebanyakan. “Dan resiko memiliki pemimpin yang tidak mengerti agama,” kata seorang ustadz, ahad pagi ini. Ditambah dengan ulama yang takut pada penguasa sehingga tidak menyampaikan sesuatu yang benar kepada pemimpinnya. Karena ditengarai sesungguhnya pemimpin tertinggi di republik ini orangnya terbuka dan mau mendengarkan. Tapi sayangnya kurang tegas.
Saya berharap bahwa kengototan pemerintah untuk tetap berlebaran pada hari Rabu bukan didasari karena tidak mau mengubah hari libur, nasionalisme yang sempit, pemikiran sekuler yang hinggap di tubuh kementerian yang mengurusi agama di republik ini, yang ujungnya tidak mau sehaluan dengan orang-orang yang menurut mereka berpemahaman transnasional, atau tak mau mengubah protokoler yang sudah disiapkan para pembantu pemimpin itu. Namun semata-mata karena pertimbangan fikih yang matang.
Singapura yang sekuler dan mayoritas nonIslam saja mau menggeser hari liburnya di hari Selasa lalu mengapa kita yang mayoritas tidak bisa?
Saya berharap pula di tahun-tahun mendatang tidak terjadi perbedaan lagi. Karena yang repot kita-kita di bawah ini. Setiap tahun berdebat lagi. Setiap tahun memberikan penjelasan lagi. Bila tidak ditangani dengan baik khawatirnya umat menjadi bercerai-berai. Pemerintah tak perlu mengorbankan kita lagi untuk hal ini.
Katanya satu atau dua tahun ke depan pemerintah mengusahakan untuk dapat menyamakan cara penghitungan penentuan tanggal hari raya antarormas Islam. Syukurlah kalau begitu.
“Oleh karenanya pilihlah pemimpin yang mengerti agama dan isilah parlemen dengan orang-orang yang tak sekadar KTP-nya Islam,” tambah ustadz kami menutup pengajian shubuh ini. Betul juga sih kata ustadz itu, pemimpin yang mengerti agama akan dengan mudah fleksibel dan juga tegas dalam berprinsip. Orang-orang yang mengerti agama dalam parlemen pun akan bisa saling nasehat menasehati dalam kebaikan kepada pemerintah. Pastinya produk undang-undang yang dihasilkan selalu membela kepentingan umat. Insya Allah.
Wallohua’lam bishshowab. Hanya Allah yang Mahacerdas lagi Maha Mengetahui.
Maraji’:
100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari, Dr. Abdul karim Zindan, Penerjemah: Muhyiddin Mas Rida, Lc., Penerbit Pustaka al-Kautsar, Cet. I, Februari 2008
Riza Almanfaluthi
dedaunan di ranting cemara
07.48 12 November 2010
Bagikan Tulisan Ini Jika Bermanfaat: