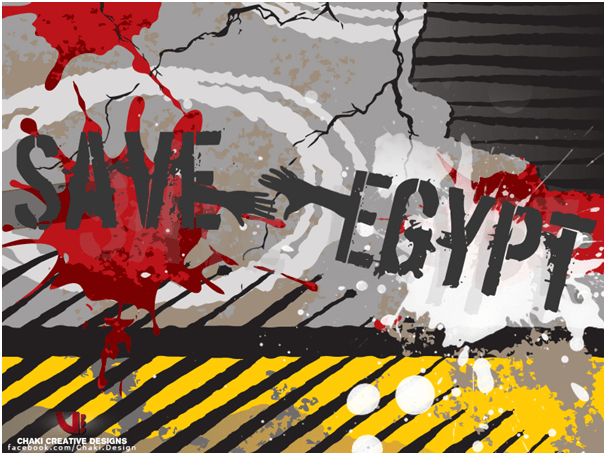TAPAKTUAN STONES UNTUK DJP BERSIH

Anggota Tapaktuan Stones dalam sebuah ekspedisi (Foto koleksi teman).
Pencanangan Gerakan DJP Bersih di Tangan Kita menjadikan dan menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memang tidak bersih di mata masyarakat. Pun, ini menyangsikan serta menyepelekan tekad dan upaya bersih yang sudah dilakukan selama ini oleh para pegawai DJP.
Inilah salah satu pernyataan yang mengemuka dari peserta sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-10/PJ/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Pembentukan Gerakan “DJP Bersih di Tangan Kita” di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut Keputusan) pada hari Jumat, 28 Maret di Kantor Wilayah DJP Aceh.
Pernyataan tersebut wajar diajukan namun tanggapannya juga layak didengarkan. Latar belakang pencanangan Gerakan adalah karena masih maraknya sebagian oknum pegawai DJP yang tidak mau menegakkan integritasnya. Beberapa di antaranya, di bulan April 2013 ada oknum pegawai DJP yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di Stasiun Gambir, berselang hampir lima minggu kemudian dua oknum lainnya tertangkap oleh institusi yang sama di Bandara Soekarno-Hatta. Belum lagi dari tahun 2010 sampai dengan 2012 tercatat lima kasus oknum pegawai pajak yang terekspos besar-besaran oleh media.
Maka wajar kita yang sedang belajar bersih ini pun geram. Pencanangan Gerakan DJP Bersih di Tangan Kita pada tanggal 5 Juli 2013 menjadi awal pemahaman baru bahwa mereka yang tidak bersih itu sebenarnya sedikit sedangkan yang baik-baik ini banyak namun tidak bisa berbuat apa-apa karena hanya diam saja. Oleh karena itu Gerakan ini menggugah orang-orang baik agar tidak tinggal diam. Orang-orang baik ini harus terorganisasi agar bisa mengalahkan mereka yang tidak mau berubah dan sedikit tapi terorganisasi itu.
Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan kalau kebatilan yang terorganisasi akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisasi. Kita pun diingatkan dengan apa yang dikatakan Muhammad Natsir suatu ketika, “Anda tahu apa yang dibutuhkan kebatilan untuk menang? Kebatilan akan menang jika pendukung kebenaran hanya diam.” Napoleon Bonaparte pernah mengatakan hal yang sama, “The world suffers a lot not because of violence of bad people but of the silence of good people.“
Dan Gerakan ini sesungguhnya memfasilitasi keengganan dari orang-orang baik ini ketika tidak mau secara personal melaporkan penyimpangan yang terjadi melalui sistem yang sudah ada, seperti whistle blowing system DJP. Dengan mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini, maka Gerakan mengidentifikasi, mendiskusikan, dan menyepakati secara bulat dan bersama-sama—ini yang perlu digarisbawahi—adanya dugaan praktik korupsi lalu melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pajak.
Pada akhirnya, dengan kenyataan sebenarnya bahwa orang-orang baik ini begitu banyak di DJP maka Keputusan ini adalah sebuah negasi penyangsian dan penyepelean tekad serta upaya bersih yang telah dilakukan bersama-sama oleh kita semua. Keputusan ini benar-benar mendorong agar orang-orang baik yang mempunyai integritas dan semangat antikoruptor yang sama ini berkumpul, tidak diam saja, saling mengingatkan, saling mengawasi, dan membuat ruang untuk melakukan pelanggaran semakin tidak ada atau hilang sama sekali.
Tapaktuan Stones
Gerakan DJP Bersih di Tangan Kita dipelopori oleh peserta aktif dari Change Agent DJP, Motor Penggerak Integritas dan berbagai komunitas keagamaan seperti Dewan Kemakmuran Masjid, Oikumene, dan Pesantian. Komunitas-komunitas ini menjadi plasma gerakan sedangkan inti gerakan adalah Direktorat Kitsda dan Unit Kepatuhan Internal. Ada yang menarik ketika berbicara komunitas. Terutama pada diktum keempat dan kelima Keputusan di atas.
Diktum keempat menyatakan bahwa: “Untuk selanjutnya, Gerakan dibentuk di unit-unit DJP di seluruh Indonesia dan keanggotaannya dapat diperluas dengan komunitas lainnya yang ada di DJP atau perseorangan pegawai DJP, yang memiliki integritas dan semangat anti koruptor yang sama.”
Sedangkan diktum kelima menyatakan, “Gerakan merupakan satu kesatuan hasil leburan dari berbagai komunitas atau perseorangan pegawai DJP sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dan Keempat.
Dari dua diktum tersebut maka dapat dikatakan bahwa komunitas apa pun yang ada di DJP entah itu formal atau pun informal dapat menjadi anggota gerakan. Genjot Pajak yang merupakan komunitas Pegawai Pajak bersepeda juga bisa menjadi anggota gerakan. Begitu pula dengan DoF (DJP Own Fotobond) yaitu komunitas fotografi karyawan DJP di seluruh Indonesia. Dan tentu dengan komunitas lainnya asal punya dua parameter berikut: berintegritas dan semangat antikoruptor.
Di Tapaktuan, awal tahun 2014 ini, telah terbentuk komunitas pecinta batu pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tapaktuan. Komunitas yang mencari batu-batu akik di seputaran Kabupaten Aceh Selatan dan menjadikan batu itu sebagai cincin. Banyak pegawai KPP Pratama Tapaktuan tergila-gila batu sekarang. Di waktu senggangnya mereka berkumpul, memamerkan cincin dan batu-batu yang mereka miliki, membicarakan tentang batu, menjadwalkan waktu mengasah batu, berburu bongkahan batu di alam liar Aceh dengan serangkaian ekspedisi, dan masih banyak agenda kegiatan lainnya.
Ciri khas yang menonjol dari Tapaktuan Stones—nama komunitas batu ini—adalah kebersamaan. Terbukti andil kebersamaan mereka mampu menjadi bagian penting dari pencapaian target e-Fin dan e-Filling KPP Pratama Tapaktuan. Bukankah pada diktum lain di keputusan itu menyatakan bahwa salah satu peran dari gerakan adalah membangun semangat kebersamaan pada setiap pegawai DJP? Maka Tapaktuan Stones dengan kebersamaan, integritas, semangat antikoruptor yang sama, mempunyai potensi besar menjadi plasma Gerakan DJP Bersih di Tangan Kita di wilayah Aceh. Semoga.
Riza Almanfaluthi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tapaktuan | 13 May 2014
Tulisan ini dimuat pertama kali di Situs Intranet Portal Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pajak