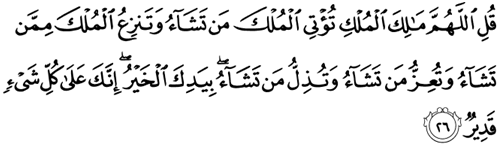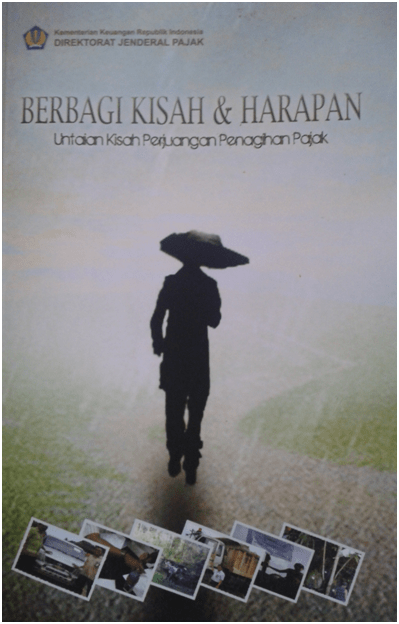RIHLAH RIZA #4: BOSCH DAN KOPI
Kita tak pernah tahu teh dan kopi panas yang kita minum di saat coffe break ternyata punya cerita panjang di balik keberadaannya. Ada banyak jejak amis darah dan pengorbanan dari nenek moyang kita.
Setelah hampir bangkrut karena terlibat perang dengan Pangeran Diponegoro, maka selama lebih dari satu abad (1935-1940) penjajah Belanda menikmati kas negara yang berlimpah dari sistem tanam paksa. Sistem ini mewajibkan setiap desa menyisihkan 20% luas tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor seperti kopi dan teh. Jika tidak punya tanah maka penduduk desa wajib bekerja selama 75 hari di kebun-kebun penjajah. Inilah era yang dikenal sebagai era paling menindas dari penjajah Belanda di bumi pertiwi ini. Bahkan lebih kejam daripada VOC yang bangkrut duluan karena korupsi itu.
**
Ini masih di hari kedua di Banda Aceh. Setelah acara pelantikan dan rapat bersama Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Aceh, saya bersama dengan dua orang teman yang juga ditempatkan di Tapak Tuan bertemu dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tapak Tuan Pak Jaelani. Kami memperkenalkan diri kepadanya. Singkat cerita, untuk lebih mengakrabkan diri, Pak Jaelani mengajak kami ngupi-ngupi nanti malam di kedai kopi. Tentunya kami bersedia.
Setelah bertemu dengan Pak Jaelani, saya menyempatkan diri bertemu dengan teman lama yang asli Aceh. Ia satu angkatan dengan saya di STAN Prodip Keuangan dulu. Kalau di grup Whatsapp kami, namanya Opa Lucu. Nama sebenarnya Nova Yanti. Sejak lulus sudah ditempatkan di Banda Aceh. Sekarang dia sebagai Penelaah Keberatan di Kanwil DJP Aceh. Dua teman saya yang sama-sama berangkat dari Jakarta, Slamet Widada dan Agung Pranoto Eko Putro, sudah silaturahmi duluan dengannya. Saya belakangan dan cuma sebentar ketemu Opa Lucu karena sudah ditunggu rombongan untuk pulang ke penginapan. Tak apalah, yang penting silaturahminya sudah. Itukan bikin panjang umur dan tambah rezeki kita.
Kami sampai di Hotel Medan maghrib. Hujan masih turun. Saya rehat sejenak. Sehabis makan malam saya menunggu jemputan untuk ngupi-ngupi itu. Jarum jam pendek udah melewati angka tujuh, lalu angka delapan, dan angka Sembilan. Tidak ada informasi jadi atau tidaknya. Sepertinya memang menunggu hujan dan gerimisnya reda. Baru pada pukul 21.46 ada informasi kalau jemputan akan datang ke Hotel Medan. Setengah jam kemudian saya telah berada di dalam mobil yang di dalamnya sudah berisi lima orang.
Ternyata ada Mas Hidra Simon yang nyetir. Mas Hidra Simon ini adalah Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV di KPP Pratama Banda Aceh. Wajahnya tak asing karena pernah kami undang untuk bersama-sama menghadiri persidangan banding di Pengadilan Pajak atas kasus sengketa pajak yang kami tangani sewaktu saya masih di Direktorat Keberatan dan Banding. Di sampingnya duduk Mas Afrizal Kurniawan Syarief, satu kantor dengan Mas Hidra Simon. Ia Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III.
Selain itu ada Mas Oji Saeroji. Teman yang ditempatkan di KPP Pratama Tapak Tuan bersama-sama saya. Di KPP itu ia menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan. Ia adalah salah satu penulis Buku Berbagi Kisah dan Harapan (Berkah) Perjalanan Modernisasi Direktorat Jenderal Pajak. Ketemu pertama kali waktu ada workshop kepenulisan buat para kontributor Buku Berkah di akhir 2010. Terakhir ketemu waktu ada workshop Tax Knowledge Base di Bandung akhir Mei 2013. Dan dunia itu kecil. Sempit. Karena ternyata dia kenal juga dengan teman SMA saya. Alamaak…
Ada lagi yang sama-sama ditempatkan di Tapak Tuan, Mas Suardjono. Ia jadi Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan di KPP Pratama Tapak Tuan. Terakhir adalah Mas Maman Purwanto. Ia orang baru yang ditempatkan di KPP Pratama Subulussalam sebagai Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan juga. Jadi selain Mas Hidra Simon dan Mas Afrizal, kami berempat adalah orang baru di daerah Aceh ini.
Kami tiba di sebuah warung kopi besar: Aan ‘n Adua Kupi. Ada layar lebar seperti layar tancap. Yang diputar adalah film-film tv kabel. Sound system-nya gede. Warung ini berfasilitas wifi. Sudah banyak orang di warung itu. Kebanyakan anak muda dengan laptop masing-masing. Asap rokok pun membumbung ke mana-mana. Pak Jaelani bersama dua anaknya dan dua keponakannya sudah menunggu di warung. Pak Jaelani ini memang orang asli Aceh, setiap akhir pekan beliau pulang dari Tapak Tuan karena keluarganya tinggal di Banda Aceh.

Gambar kopi dari sini.
Saya pesan kopi biasa. Teman-teman yang lain pesan kopi sanger (kopi susu). Selain kopi dihidangkan pula roti dan gorengan tempe dalam sebuah piring kecil. Sambil ngupi-ngupi itu kami mengobrol lama. Ada rencana yang tersusun akhirnya. Nanti hari minggu Mas Oji dan Mas Suardjono akan berangkat ke Tapak Tuan satu mobil bersama Pak Jaelani. Berangkat jam sepuluh pagi dari Banda Aceh. Diperkirakan sampai di Tapak Tuan jam tujuh malam. Sedangkan saya masih memikirkan moda transportasi alternatif menuju Tapak Tuan pada satu pekan yang akan datangnya. Karena ada penugasan lain dari kantor lama saya baru satu minggu kemudian menyusul dua teman saya itu ke Tapak Tuan. Pak Jaelani sudah menawarkan saya untuk ikut mobilnya. Saya belum mengiyakan cuma tak enak saja karena takut merepotkan lagi.
Malam semakin larut. Akhirnya pertemuan silaturahmi awal ini pun selesai. Saya cuma bisa meminum segelas kopi saja. Tapi alhamdulillah lambung tak menolak seperti biasanya. Kami pulang. Pak Jaelani khawatir kalau ngupi-ngupi nya dilanjutkan lebih malam lagi, kami tak bisa beristirahat terutama saya yang kudu balik lagi ke Jakarta.
Warung kopinya tetap buka. Saya tak tahu kapan tutupnya. Warung kopi tak bisa dilepaskan dari kehidupan malam masyarakat Aceh. Pun kopi yang kami minum tadi. Ini warisan kerja rodi nenek moyang masyarakat Aceh sejak tanam paksa. Kita tinggal menikmatinya. Kita tak tahu tragedi apa yang ada di balik setiap tanaman kopi yang dipaksakan ditanam oleh penjajah Belanda ini. Seperti kita tak tahu pula tragedi apa yang dialami oleh nenek moyang kita dari setiap baut dan kayu jati yang tertempel di rel kereta api sepanjang utara Jawa.

Tanam Paksa (Gambar diambil dari sini)
Tapi yang pasti betapa banyak korban dari kekejaman sistem tanam paksa ini. Busung lapar dan kelaparan melanda Cirebon, Demak, dan Grobogan. Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pencetus cultuurstelsel malah dianugerahi gelar kebangsawanan Graaf atas jasa-jasanya dalam penerapan sistem kejam ini. Tapi karena perubahan politik di negeri penjajah itu sendiri, maka sistem tanam paksa dicabut di tahun 1870. Mekipun demikian era ini belumlah berakhir untuk daerah di luar Jawa. Penjajah Belanda mengembangkan penanaman besar-besaran yang difokuskan pada tanaman kopi. Contohnya di Tanah Gayo, Aceh, sejak tahun 1904.
Sekarang produksi kopi menjadi tulang punggung sebagian masyarakat Aceh terutama di Aceh Tengah dan Bener Merah. Dari data terakhir di tahun 2012 Aceh menjadi daerah penghasil kopi terbesar keenam setelah Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Bengkulu.
Catatan ini sudah terlalu panjang. Saatnya mengakhirinya dengan satu pesan: kini berpikirlah sejenak saat kita meminum kopi. Karena ada masa lalu yang mengikutinya.
***
Riza Almanfaluthi
dedaunan di ranting cemara
5:41 26 Oktober 2013
Thanks to: Mas Hidra Simon dan Afrizal Kurniawan Syarief karena telah mengantar kami untuk ngupi-ngupi. Thanks to Opalucu karena telah menerima kami.
Tags: Hidra Simon, Suardjono, oji saeroji, jaelani, kepala KPP Pratama Tapak Tuan, afrizal kurniawan syarief, maman purwanto, kpp pratama banda aceh, kpp pratama tapak tuan, kpp pratama subulussalam, aan ‘n adua kupi, opa lucu, nova yanti, @opalucu, slamet widada, agung pranoto eko putro, Johannes van den bosch, cultuurstelsel, cultuur stelsel, hotel medan, pangeran diponegoro, tanah gayo, kopi aceh, kopi gayo, graaf,